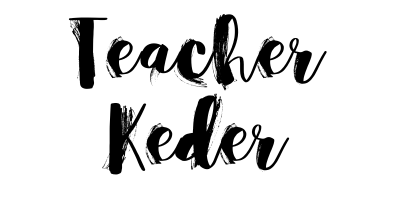Berjibaku di Jambore GTK - Wawancara #2
Setelah semalaman nggak bisa tidur nyenyak karena dikabarin Bu Sof, salah satu rekan guru, yang dapat chat WA dari BBGP Jawa Tengah, saya langsung berangkat ag…
Berjibaku di Jambore GTK #1
Masih nggak nyangka, kalau belakangan ini akan menjadi hari-hari yang sangat sibuk bagi saya. Mengingat di bulan-bulan sebelumnya kehidupan saya lebih banyak d…
Tiba-Tiba Ngomongin Guru Penggerak
Rasanya udah lama banget saya nggak nulis di blog ini. Setiap ngerasa ada kesibukan, saya pasti susah buat membagi waktu, padahal sebenernya ‘kesibukan’ itu ju…
Silaturahmi Ke Xiaomi Service Center
Beberapa waktu lalu, Pak Ujang, yang sampai saat ini masih jadi guru di sebuah SDIT, tiba-tiba ngechat WA mau minta tolong beliin HP lewat online . Memang, bag…
Refreshing Kelabu
Hari Jum’at, 24 November, saya bersama ‘komplotan ghibah’ (beberapa guru SDIT dan penyintas yang dulu pernah ngajar bareng di sebuah SDIT, yang saya tulis ceri…
Komplotan Ghibah di Bukit Bintang, Guci
Momen bersejarah itu terjadi pada hari Sabtu kemarin, di mana para bapak-bapak keder akhirnya bisa pergi ngecamp bareng. Setelah bertahun-tahun lamanya wacana …
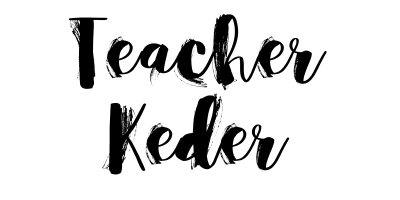




.jpg)