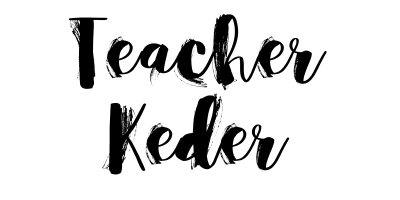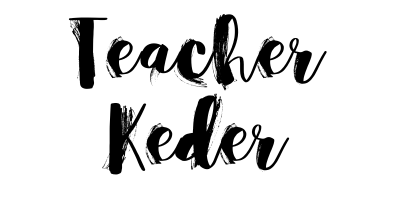Menampilkan postingan dari Juli, 2017Tunjukkan semua
Suka-Suka Ngomongin Toko Komik Online
Waktu kecil, gue hobi banget main ke persewaan buku dan komik buat nyewa komik bareng temen-temen. Bahkan saking seringnya baca komik, B apak gue di rumah sa…
Footer Menu Widget
Copyright ©
Diary Teacher Keder